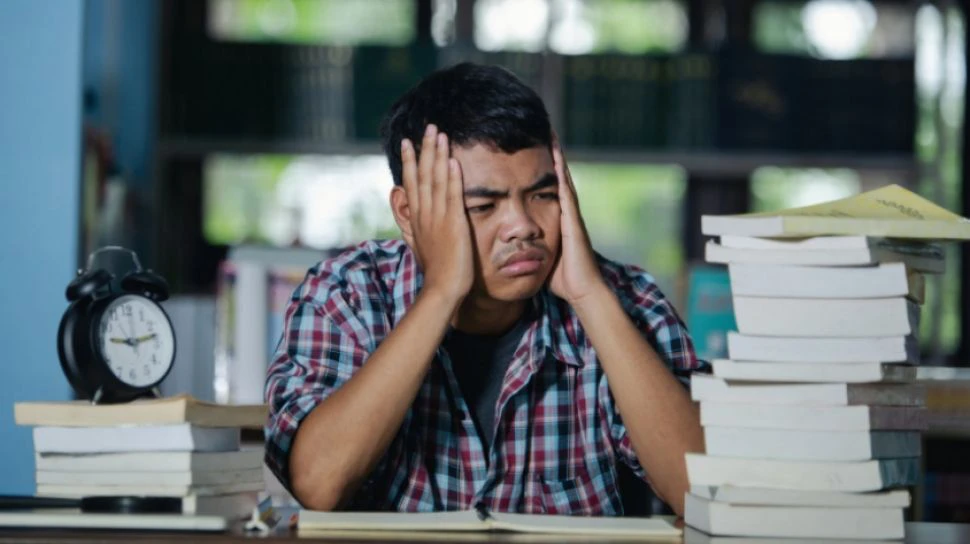
Duck Syndrome: Saat Seseorang Terlihat Tenang, Tapi Berjuang di Bawah Permukaan
BANDUNG INSPIRA – Di luar, ia tersenyum, aktif berpendapat di kelas, dan selalu hadir dalam berbagai kegiatan kampus. Di media sosial, prestasi akademik, kegiatan organisasi, hingga foto liburan berjejer rapi, menciptakan citra mahasiswa yang serba bisa.
Namun, yang tak terlihat adalah jam-jam panjang begadang, rasa cemas yang tak kunjung reda, dan pikiran yang terus berputar memikirkan target berikutnya.
Fenomena ini dikenal sebagai duck syndrome—metafora seekor bebek yang tampak meluncur anggun di permukaan air, padahal di bawahnya kakinya mengayuh panik agar tetap mengapung.
Istilah ini pertama kali muncul di Stanford University. Namun kini, menurut Anisa Yuliandri, S.Psi., M.Psi., Psikolog dari Career and Student Development Unit (CSDU) FEB UGM, semakin sering ditemukan di kampus-kampus Indonesia.
“Banyak mahasiswa yang berusaha memenuhi ekspektasi tinggi, baik dari diri sendiri maupun lingkungan. Mereka mempertahankan IPK, ikut organisasi, magang, lomba, bahkan tetap aktif di media sosial. Takut tertinggal membuat mereka merasa harus ambil semua kesempatan,” katanya seperti dikutip dari laman resmi UGM.
Anisa menjelaskan, menurut Self-Determination Theory, manusia memiliki tiga kebutuhan psikologis dasar: otonomi, rasa mampu, dan keterhubungan.
Duck syndrome sering muncul ketika pilihan hidup lebih didorong oleh tekanan luar ketimbang keinginan pribadi. Hasilnya, keseimbangan mental pun terganggu.
Budaya “selalu terlihat baik-baik saja” memperparah keadaan. Banyak mahasiswa menekan perasaan lelah atau sedih demi mempertahankan citra sempurna.
Sikap perfeksionis ini, ditambah paparan media sosial yang penuh pencapaian orang lain, menciptakan tekanan baru.
“Mereka ingin terlihat kuat dan produktif meskipun sebenarnya sedang kelelahan,” kata Anisa, merujuk pada Impression Management Theory—konsep bahwa seseorang kerap mengatur citra diri agar sesuai dengan harapan publik.
Masalahnya, duck syndrome kerap tak kasat mata. Kalimat seperti “semua orang juga capek” atau “kalau mau sukses memang harus begini” menjadi pembenaran untuk terus memaksakan diri.
Jika dibiarkan, kondisi ini bisa berkembang menjadi kecemasan kronis, insomnia, burnout, bahkan depresi. Gejala lainnya termasuk menarik diri dari pergaulan dan merasa tidak cukup baik. “Yang dibutuhkan sering kali bukan solusi instan, tapi ruang untuk didengar,” ujarnya.
Anisa menekankan pentingnya mengenali sinyal-sinyal awal. Langkah pertama adalah kejujuran pada diri sendiri—mengakui rasa lelah bukanlah kelemahan.
“It’s okay to not be okay. Kita tidak harus selalu produktif atau terlihat bahagia. Memberi izin pada diri untuk merasa sedih adalah bagian dari pemulihan,” jelasnya.
Selain itu, mengelola ekspektasi menjadi kunci. Tidak semua standar harus diikuti, dan menolak suatu tanggung jawab demi kesehatan mental adalah sah. “Belajar mengatakan ‘tidak’ tanpa rasa bersalah adalah keterampilan penting,” tambahnya.
FEB UGM, melalui CSDU, menyediakan layanan konseling gratis serta Program Peer Support—teman sebaya yang dilatih untuk menjadi pendengar aman dan suportif. Anisa berharap mahasiswa berani memanfaatkannya.
“Kalau hari ini yang bisa kita lakukan hanyalah bertahan, itu sudah cukup. Bertahan juga bentuk keberanian,” tutupnya. (Tim Berita Inspira)**



